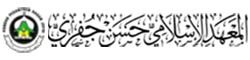Para ulama yang tiba di Nusantara menjalankan strategi dan
metode dakwah dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Tindakan ini dilakukan
sebagai respons terhadap tantangan berat dalam menyebarkan dakwah di Nusantara
pada masa lalu, terutama dengan adanya kelompok Bhairawa Tantra.
Selama berabad-abad, para pendakwah Islam menghadapi
tantangan berat ketika memasuki Tanah Jawa dan sebagian wilayah Nusantara.
Salah satu tantangannya adalah keberadaan sebuah sekte yang dikenal sebagai
Bhairawa Tantra.
Bhairawa Tantra merupakan hasil dari perpaduan agama dan
pemahaman tertentu dalam suatu sintesis yang bersifat sinkretis. Hal ini
melahirkan aliran Tantrayana atau Bhairawa Tantra yang melibatkan ritual-ritual
amoral dan mengakibatkan kemuraman dalam peradaban selama beberapa abad (lihat
Widji Saksono, "Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Atas Metode Dakwah
Walisongo", Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hal. 223-224).
Istilah "Tantrayana" digunakan karena aliran ini,
yang awalnya berasal dari kelompok Çakta, menggunakan kitab suci yang disebut
Tantra sebagai pedoman. Kitab ini berisi berbagai aspek keagamaan dan ritual,
termasuk unsur-unsur sihir dan kegaiban.
Mantra, jampi, simbol-simbol mistik, dan benda-benda mistik
lainnya memainkan peran penting dalam usaha manusia untuk mencapai persatuan
dengan Tuhan (Drs. R. Soekmono, "Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia
2", Cetakan V, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988, hal. 34).
Bhairawa Tantra juga sering disebut Bhairawatantra karena
pemujaannya yang ditujukan kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa dipandang sebagai
Mahadewa (Dewa Tertinggi), Maheçwara (Maha Kuasa), dan Mahakala (Sang Waktu)
dalam Trimurti. Siwa dianggap sebagai dewa yang sangat berkuasa atas waktu,
yang mengadakan, melangsungkan, dan mengakhiri. Pemujaan terhadap Siwa selalu
disertai dengan permohonan, harapan, dan rasa takut yang mendalam. Siwa juga
dianggap sebagai Mahaguru dan Mahayogi yang menjadi teladan dan pemimpin bagi
para petapa. Khususnya, Siwa dipuja sebagai Bhairawa, salah satu aspek
perwujudannya yang memiliki kekuatan untuk mengakhiri kehidupan dan segala yang
ada (Drs. Soekmono, "Pengantar Sejarah...", Ibid., hal. 29).
Bhairawa Tantra mewakili bentuk sinkretisme antara Siwa dan
Budha, berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa. Pandangan utama dari aliran
ini adalah bahwa dengan mengikuti hawa nafsu, jiwa manusia pada akhirnya akan
lebih mudah diarahkan untuk menjauhi dorongan-dorongan tersebut.
Menurut ajaran Bhairawa Tantra, manusia sebaiknya tidak
menahan nafsu, bahkan sebaiknya memperturutkan hawa nafsu. Sebab, menurut
keyakinan ini, kepuasan nafsu akan membawa kebebasan bagi jiwa manusia (Dr.
Prijohutomo, "Sedjarah Kebudajaan Indonesia I: Bangsa Hindu", J.B.
Wolter, Jakarta-Groningen, 1953, hal. 89).
Ritual seks bebas mengambil bentuk yang dikenal sebagai
ma-lima atau pancamakara. Ritual Ma-lima ini terdiri dari matsiya (ikan), mamsa
(daging), mada (minuman keras), mudra (ekstase melalui tarian erotis atau
melibatkan makhluk halus hingga "kerasukan," juga mencakup sikap
tangan yang dianggap memunculkan kekuatan gaib), dan maithuna (seks bebas).
(Referensi: Prof. Dr. H. M. Rasjidi, "Islam dan Kebatinan," Jajasan
Islam Studi Club Indonesia, Jakarta, 1967, hal. 68. Lihat juga Drs. R.
Soekmono, "Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2," Cetakan V,
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988, hal. 33-34).
Dalam bentuk yang paling esoterik, pemujaan yang bersifat
Tantrik melibatkan persembahan manusia, termasuk meminum darah dan memakan
dagingnya sebagai bagian dari ritual. (Referensi: Paul Michel Munoz,
"Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung
Malaysia," Terjemahan, Mitra Abadi, Yogyakarta, 2006, hal. 253 dan 448).
Ritual seks bebas dan konsumsi minuman keras juga dilakukan
di tempat peribadatan, seperti lapangan (padang) yang dikenal sebagai Lemah
Citra atau Setra. Tujuan dari ritual ini adalah untuk memperoleh çakti. Oleh
karena itu, aliran ini sering disebut sebagai saktiisme. Sisa-sisa ajaran ini
masih dapat ditemui di Jawa dengan istilah kasekten atau kesaktian. (Referensi:
Prof. Dr. Koentjoroningrat (ed.), "Manusia dan Kebudayaan di
Indonesia," Cetakan XXI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 347).
Ritual persetubuhan (maithuna) dalam Bhairawa Tantra mungkin bersumber dari pandangan sebagian agama yang ada di Indonesia pada masa tersebut, di mana hubungan kelamin dipandang memiliki makna mistik. Hubungan seksual tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga suami-istri, tetapi juga melibatkan hubungan seksual dalam konteks upacara keagamaan.
Praktik persetubuhan ini diartikan sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan, mencakup harapan akan turunnya hujan, hasil panen yang melimpah, perkembangan ternak, atau digunakan untuk pertahanan secara magis. Dalam upacara mahavarata, seorang murid (brahmacarin) terlibat dalam persetubuhan dengan seorang perempuan pelacur (punmcali) di dalam ruangan yang diadakan untuk berkorban. Perempuan yang telah diberkati dengan mantra juga dianggap sebagai wujud tempat korban. Dengan demikian, hubungan seksual dianggap sebagai manifestasi dari ibadah kurban.